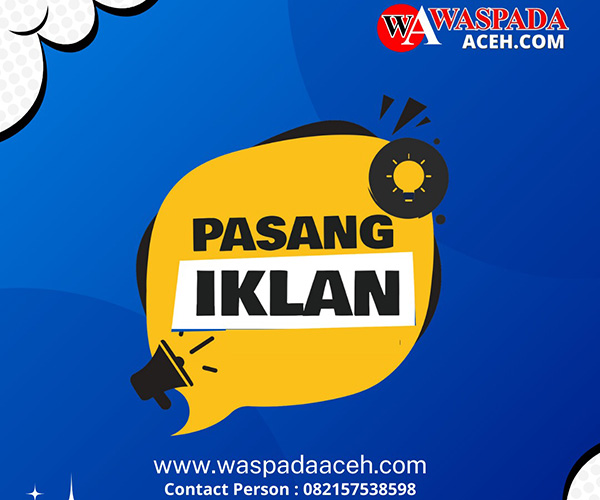Di Aceh, iming-iming kerja di kapal asing telah menjerat banyak pemuda dalam jaringan eksploitasi yang kejam.
Di banyak desa di Aceh, selembar surat bermaterai bisa berubah jadi jebakan. Dokumen yang disebut “surat mengetahui” itu seolah hanya formalitas, cukup ditandatangani keuchik (kepala desa) sebagai bukti izin orang tua. Namun justru di situlah jalan masuk perdagangan orang terbuka.
Tujuh tahun berlalu, Muzakir Walad, mantan Kepala Desa Kuta Blang, Lhokseumawe, baru menyadari bahwa tanda tangannya di selembar surat telah membuka jalan warganya, Zulfahmi, masuk perangkap dalam jaringan perdagangan orang. Niatnya membantu warga keluar dari jerat kemiskinan justru berakhir sebaliknya.
“Oh, Zulfahmi yang kerja di kapal? Ya Allah… baru sekarang saya tahu dia korban,” ucap Muzakir pelan. Matanya tertuju pada layar ponsel yang menampilkan salinan surat bermaterai yang pernah ia tanda tangani tujuh tahun lalu.
Di salah satu warung kopi di Lhokseumawe, pada Jumat malam (14/6/2025), Muzakir duduk, tatapannya kosong. Ia menarik napas panjang, seakan menahan sesal.
Biasanya, kata Muzakir, orang tua datang membawa surat pernyataan izin untuk anak mereka. Tugas keuchik hanya menandatangani sebagai bentuk mengetahui, tanpa syarat apa pun. “Itu saja. Tidak pernah ada aturan khusus,” tutur mantan Keuchik Kuta Blang Periode 2018-2024 itu.
Zulfahmi, yang duduk di samping Muzakir, membenarkan. Surat itu dibawa ibunya sebagai syarat keberangkatan. “Iya, betul. Mamak saya yang urus,” ujarnya tenang.
Di atas kertas bermaterai Rp6.000 berkop PT RCA itu, tertera izin orang tua bagi anaknya bekerja di kapal ikan Taiwan atau China. Tak ada informasi soal gaji, jam kerja, asuransi, maupun mekanisme pengaduan. Sebaliknya yang ada justru pasal berat: keluarga wajib mengganti kerugian bila Zulfahmi mundur, tak boleh menuntut bila terjadi masalah di kapal, dan dikenakan denda 3.000 dolar AS bila ia kabur.
“Yang saya harapkan warga terbantu, saya tidak berpikir kalau ternyata malah terjadi sebaliknya,” ujarnya.
Selama menjabat kepala desa, Muzakir tak pernah mendapat sosialisasi resmi soal pencegahan perdagangan orang dari institusi manapun.

“Kalau sosialisasi khusus soal kerja luar negeri atau TPPO, belum pernah. Urusan administrasi memang untuk memudahkan warga, tapi kami tidak tahu mereka akhirnya dikirim ke mana dan bekerja di mana,” ujarnya
Ia menyayangkan belum ada sistem data rapi antar instansi. “Kalau ada edukasi kami dukung, biar anak-anak desa tak tertipu janji palsu lagi,” ucapnya.
Zulfahmi (31) salah satu di antara banyak anak muda di daerah itu yang menerima tawaran bekerja di kapal penangkap ikan berbendera asing.
Pada September 2019, seorang teman yang baru pulang dari kapal penangkap ikan mengajaknya bergabung. Saat itu, peluang kerja di kampungnya makin sempit. Cerita tentang gaji besar di kapal asing terdengar seperti jalan keluar.
“Saya lihat dia bawa uang lumayan, jadi saya tertarik,” kenangnya.
Lewat temannya, ia mendapat kontak PT RCA dan diminta menyiapkan berkas: surat persetujuan orang tua, paspor, ijazah, kartu keluarga, akta kelahiran, dan SKCK. Sementara dokumen lain seperti BST, buku pelaut, dan medical check up diurus perusahaan.
Prosesnya cepat. Dari Aceh, Zulfahmi berangkat ke Tegal, markas manning agency, lalu diterbangkan ke Singapura sebelum ditempatkan di kapal Lu Qing Yuan Yu 329 berbendera China.
Zulfahmi dioper ke sejumlah kapal, bekerja tanpa batas waktu, minim makanan, dan sering mendapat perlakuan kasar. Pada 2021, setelah ia bersama kawan-kawan melancarkan protes, mereka dipulangkan secara tidak resmi melalui jalur tikus di Batam. Gaji hanya dibayar sebagian kecil bahkan tidak sampai dari 50 persen yang seharusnya diterima, dokumen ditahan perusahaan. Kasus ini tak pernah tercatat, apalagi ditindaklanjuti aparat hukum.
Celah dari Desa
Kisah Zulfahmi bukan satu-satunya potret kelam jeratan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di kapal perikanan asing. Di Aceh, modus serupa terus berulang, bahkan melibatkan lingkar terdekat warga, yaitu kepala desa.
FS, warga Aceh Utara, terjebak TPPO setelah menerima tawaran kerja dari Pj Keuchik pada November 2018. Ia dijanjikan gaji besar di kapal asing tanpa penjelasan risiko maupun legalitas.
“Saat itu ekonomi sulit, saya kerja serabutan. Karena pernah melaut, saya tertarik,” ujarnya.
Hubungan keluarga dengan sang Pj Keuchik R membuat FS semakin percaya. Informasi awal perekrutan bahkan disebut-sebut datang dari seorang guru di Lhokseumawe berinisial M. Perusahaan yang merekrutnya adalah PT RMB.
Sebelum berangkat, FS harus mengeluarkan biaya besar untuk paspor dan dokumen hingga ia harus berhutang. Tarif paspor lebih mahal dari harga resmi dengan alasan agar namanya tidak masuk daftar hitam.
Sementara dokumen penting, seperti Basic Safety Training (BST) dan buku pelaut, diurus tanpa pelatihan.“Tidak ada pelatihan, tahu-tahu dokumennya sudah keluar,” kata F.
Tiga bulan kemudian, bersama 53 orang lain, ia diberangkatkan ke Garut untuk menandatangani perjanjian kerja laut (PKL) dengan gaji USD 350 per bulan dan pola kerja delapan bulan di laut serta empat bulan cuti. Dari sana, mereka diterbangkan ke China. FS ditempatkan di kapal penangkap cumi Zhou Yu 907.
Awalnya, FS optimis. Ia terbiasa menghadapi kerasnya hidup di laut. Tetapi kenyataan jauh dari janji manis. Selama tiga bulan pertama, ia hanya menerima USD 50 per bulan. Sisanya ditahan, kata pihak kapal, sebagai “jaminan” sebesar USD 900. Biaya atribut kerja dipotong, bonus tangkapan tak pernah dibayar, dan jam kerja bisa berlangsung hampir 24 jam tanpa tambahan upah.
Masalah semakin parah ketika kontrak habis. Alih-alih mendapat cuti, FS dan kawan-kawan justru dipaksa bekerja di darat untuk mengemas hasil tangkapan. Perusahaan bahkan diduga “menjual” para ABK ke pihak lain, di luar kontrak yang telah disepakati. Uang jaminan tak pernah kembali, bonus pun tak cair.
“Kami benar-benar diperlakukan tidak manusiawi,” ujar FS dengan nada getir.

Banyak Korban di Lhokseumawe
Kota Lhokseumawe, tercatat sebagai daerah dengan jumlah tertinggi pekerja migran asal Aceh yang terindikasi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di kapal perikanan asing.
Berdasarkan data Sumatera Environmental Initiative (SEI), sejak 2020 hingga pertengahan 2024, ada 18 orang dari kota ini yang menjadi korban kasus serupa. Posisi kedua ditempati Kabupaten Aceh Utara.
Direktur Sumatera Environmental Initiative (SEI), Masykur Agustiar, mengatakan fakta-fakta ini jelas bertabrakan dengan mandat UU 18/2017 yang menempatkan desa sebagai ujung tombak pencegahan TPPO.
“Desa seharusnya jadi pintu pertama perlindungan bagi PMI (Pekerja Migran Indonesia), termasuk yang bekerja di kapal perikanan asing. Sayangnya, kepedulian desa masih lemah. Negara hadir di level regulasi, tapi absen di akar rumput,” ujarnya
Menurutnya, indikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bisa dilihat sejak awal proses keberangkatan. Perlindungan mestinya dimulai ketika warga mengajukan surat rekomendasi.
“Sebelum menandatangani dokumen, pemerintah desa harus memahami perusahaan yang memberangkatkan dan memastikan legalitasnya,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, banyak kasus kontrak kerja dan informasi perusahaan baru diberikan saat pekerja sudah berada di penampungan. Padahal jalur resmi keberangkatan diatur ketat, melibatkan dinas tenaga kerja, agen resmi, hingga pihak imigrasi. Calon anak buah kapal (ABK) juga wajib menjalani pemeriksaan medis di klinik yang ditunjuk.
“Faktanya, banyak yang disalurkan secara ilegal,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga perlu menyediakan jalur alternatif yang sah dan aman untuk bekerja di kapal, sekaligus melibatkan desa dalam seleksi, pengawasan, dan pendampingan.
“Pada akhirnya, desa bukan sekadar sumber data administratif, melainkan penjaga pertama harapan warganya yang ingin mengubah nasib di luar negeri,” ucapnya
Desa Belum Melek Perlindungan PMI
Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Aceh juga menuding lemahnya peran desa membuat warganya rentan menjadi korban. Kepala BP3MI Aceh, Siti Rolijah mengatakan perlindungan pekerja migran bukan hanya tugas mereka, tetapi juga pemerintah gampong.
“UU Nomor 18 Tahun 2017 sudah jelas menempatkan pemerintah daerah dan desa sebagai ujung tombak edukasi, fasilitasi dokumen, dan penanganan kasus. Tapi banyak desa belum memahami, atau menganggap ini bukan prioritas,” ujar Siti.
Ia mencontohkan, ada desa yang lebih fokus ke infrastruktur ketimbang pencegahan TPPO. Padahal, biaya pemulangan satu pekerja migran bermasalah bisa mencapai miliaran rupiah. Situasi semakin rumit karena banyak warga berangkat tanpa melapor, sehingga desa tak memiliki data dasar saat muncul masalah hukum atau klaim asuransi.
“Masalah pekerja migran itu seperti gunung es. Yang terlihat sedikit, tapi di bawahnya banyak yang ilegal dan tidak terdata,” tegasnya.
Siti juga menjelaskan, BP3MI tak memiliki anggaran yang cukup untuk menjangkau seluruh desa di Aceh yang jumlahnya sekitar 6.400 desa. Karena itu, sosialisasi lebih difokuskan ke kantong-kantong pekerja migran: Aceh Utara, Bireuen, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Langsa, Pidie, Pidie Jaya, Lhokseumawe, dan Aceh Singkil.
Sebenarnya pemerintah melalui Surat Edaran Bersama (SEB) telah berupaya memperkuat peran desa. SEB itu ditandatangani oleh empat menteri pada 2024 yaitu Menteri Ketenagakerjaani, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran.
Peran desa mulai dari memfasilitasi dokumen, memastikan persetujuan keluarga, mencatat rencana keberangkatan, sampai membantu penanganan masalah di luar negeri.
“Banyak desa belum punya mekanisme pencatatan ini. Karena itu, kami dorong pemerintah kabupaten/kota segera membuat aturan turunan yang memberi pedoman teknis, termasuk penggunaan dana desa untuk pencegahan, pemberdayaan, dan pendampingan kasus,” kata Siti.
Ia mengingatkan, semua pihak harus menjalankan peran sesuai mandat. “Jangan tunggu masalah dulu baru bergerak. Kalau semua berjalan sesuai aturan, banyak masa depan yang bisa kita selamatkan,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu keuchik di Desa Mon Geudong, Lhokseumawe, Mujiburrahman mengatakan selama ini pemerintah gampong lebih fokus pada urusan yang diatur dalam UU Desa, sementara isu pekerja migran jarang tersentuh.
“Saya sendiri baru tahu ada UU Pekerja Migran yang juga menegaskan peran desa. Selama ini kami belum pernah dapat sosialisasi resmi. Semoga ke depan ada, supaya kami di desa bisa benar-benar paham aturan dan melindungi warga,” katanya, Selasa (9/9/2025).
Sejak menjabat pada 2022, ia mengatakan belum pernah menerima laporan resmi dari warganya yang berangkat bekerja ke luar negeri. Namun ia menyadari, ada beberapa warga yang mengurus paspor.
“Kalau ada yang bikin paspor, biasanya kami tanyakan untuk apa dan kemana tujuannya. Sekaligus kami imbau agar berhati-hati, karena dari berita media sering kita baca ada warga Aceh yang jadi korban,” jelasnya.
Mujiburrahman menegaskan, jika ada instruksi atau regulasi yang jelas, pihaknya siap mendukung penuh. “Kalau memang diperintahkan dan ada mekanismenya, kami bisa memplot anggaran dari APBG untuk sosialisasi maupun pendataan. Yang penting ada payung hukumnya, sehingga desa tidak berjalan sendiri-sendiri. Harapan kami juga sinergi semakin kuat antara desa, pemerintah daerah, dan BP3MI,” jelasnya.
Ancaman TPPO Masih Mengintai Desa
Peneliti Kebijakan Kelautan dan Perikanan Crisna Akbar, menjelaskan praktik tindak pidana perdagangan orang di kapal perikanan asing masih mengintai desa-desa di Aceh. Berbagai kelemahan sistemik, seperti tumpang tindih regulasi, buruknya sistem data, lemahnya pengawasan, hingga ketidakjelasan prosedur penerbitan dokumen penting, menjadi penyebab utama.
“Proses penerbitan dokumen penting, seperti paspor, buku pelaut, dan sertifikat pelatihan, sering dilakukan tanpa verifikasi ketat. Bahkan ada indikasi pemalsuan data,” ujarnya.
Banyak paspor dibuat atas alasan wisata, sehingga pengawasan menjadi sulit. Buku pelaut diterbitkan tanpa membedakan ABK kapal niaga dan perikanan, dan tidak dilakukan pengecekan latar belakang atau kompetensi. Sertifikat Basic Safety Training (BST) kerap hanya formalitas administratif, sehingga ABK tidak memahami substansi pelatihan dan bergantung pada jaringan informal, termasuk calo.
Dalam situasi darurat di laut, tidak ada standar nasional yang melindungi mereka. Meski UU No. 18/2017 ada, implementasinya di sektor kelautan masih lemah. Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi ILO 188 yang menjamin hak-hak pekerja perikanan.
Crisna menekankan perlunya pengawasan ketat sejak di desa, edukasi pekerja, dan evaluasi peran Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan serta Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mencegah praktik ilegal.
Belum ada standar upah dan kenyamanan kerja di kapal, sehingga Aceh membutuhkan gebrakan baru dalam tata kelola perekrutan dan perikanan.
Zulfahmi dan penyintas lainnya kini telah kembali ke kampung halamannya. Namun, trauma dan luka akibat malam-malam panjang di kapal tanpa perlindungan hukum masih membekas. Jebakan perusahaan terus mengintai warga yang rentan. Desa seharusnya menjadi garda pertama perlindungan, mengawal masa depan warganya. (*)
BACA LAPORAN TERKAIT:
Ketika Sekolah Jadi “Pintu” Perdagangan Orang di Kapal Asing
Jangkar Kopi, Ruang Pemulihan Penyintas TPPO di Tengah Kabut Keadilan